Pekan-pekan terakhir ini ada beberapa kabar mengenai seks di media massa: beredarnya VCD porno yang salah seorang pemerannya adalah mahasiswi UNPAD Bandung, ditolaknya klip video artis Nafa Urbach oleh stasiun televisi karena dianggap terlalu sensual, serta terbongkarnya salah satu titik pengedaran VCD porno di Jakarta Utara.
Dalam ketiga kasus itu, kebebasan arus informasi dihambat. Di Bandung, polisi dikabarkan akan menjadikan si artis VCD sebagai tersangka dalam pasal pelanggaran kesusilaan. Dalam kasus kedua, si pembuat klip diminta melakukan revisi bila ingin produknya tetap disiarkan. Sementara di Jakarta, sang pengedar ditangkap dan lebih dari seratus ribu keping VCD yang disita kabarnya akan dihancurkan.
Salah satu reaksi yang lazim muncul saat kasus-kasus semacam itu mengemuka adalah kekhawatiran atas intervensi terhadap kebebasan informasi. Dalam hal ini, argumen yang lazim muncul adalah: apakah pelarangan semacam itu sejalan dengan kepercayaan kita terhadap manusia sebagai mahluk yang dinugerahi Allah kecerdasan untuk memilih informasi? Tidakkah pelarangan semacam itu adalah pengekangan terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi? Tidakkah masyarakat seharusnya dijamin kemerdekaannya untuk mengeluarkan, menyebarkan dan menerima informasi?
Kasus mahasiswi UNPAD itu menarik. VCD itu merupakan rekaman sejumlah hubungan seks sang mahasiswi dengan teman kencannya yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dengan kata lain, mereka merekamnya dengan sengaja. Rekaman itu kemudian digandakan dan disebarluaskan, entah dengan alasan komersial atau alasan lainnya. Dengan begitu, tidakkah seharusnya hak sepasang sejoli itu dijamin atas dasar kepercayaan kita terhadap kebebasan informasi?
Umat Islam pada umumnya percaya bahwa pornografi adalah barang terlarang. Namun tetap pertanyaan di atas relevan diajukan. Apakah hanya karena umat Islam tidak boleh mengkonsumsi pornografi, produk tersebut jadinya tidak diizinkan beredar di pasar? Tidakkah pornografi bisa disejajarkan dengan babi, misalnya? Babi tidak dilarang, namun setiap makanan yang mengandung unsur babi bisa beredar secara terbuka selama menyertakan penjelasan tentang kandungan isinya, sehingga konsumen bisa menentukan sendiri apakah ia bersedia memakan makanan haram atau tidak?
Kekecualian . Untuk menjawab rangkaian argumen itu, yang perlu pertama kali diluruskan adalah pemahaman mengenai konsep kebebasan informasi. Kemerdekaan untuk mengumpulkan, menyebarkan dan menerima informasi memang adalah hak individu yang dijunjung tinggi secara universal. Namun, kemerdekaan itu tidak pernah berarti kemerdekaan absolut untuk menyebarkan infromasi apapun. Selalu ada hal-hal yang dikecualikan.
Tentu saja kekecualian itu bisa berbeda dari negara ke negara, tergantung konteks masyarakat masing-masing. Tapi marilah kita merujuk pada Amerika Serikat sebagai negara yang paling awal memberikan jaminan konstitusional atas kemerdekaan berekspresi, bicara, dan pers. Di AS, ketika orang berbicara tentang ‘freedom of speech’, ada sejumlah hal yang dinyatakan sebagai ‘unprotected speech’, dengan salah satunya adalah ‘obscenity’ (kecabulan, atau pornografi).
Jadi, berbeda dari dugaan banyak orang, pornografi sebenarnya adalah sesuatu yang terlarang di AS. Kalau kita kemudian menemukan suburnya industri seks di media di sana, itu terjadi karena longgarnya definisi pornografi yang berlaku. Sekadar gambar Cindy Crawford bertelanjang dada atau adegan ranjang Tom Cruise dan Nicole Kidman dianggap belum masuk dalam kategori ‘pornografis’. Namun adegan seks dengan kekerasan, atau yang menggunakan remaja di bawah 17 tahun, atau yang di luar ‘batas normal’ (seperti seks dengan hewan) akan dianggap sebagai produk cabul yang diancam dengan hukuman serius.
Liberalisasi definisi pornografi itu sendiri dimulai pada paruh kedua abad 20. Yang menyebabkan pelonggaran itu adalah revolusi perilaku seks masyarakat. Jadi, para era itu, konservatisme sikap terhadap seks di media dipertanyakan secara serius mengingat masyarakat secara pesat memang meninggalkan nilai-nilai kesucian seks. Dengan kata lain, mengapa seks masih harus dihambat terjaja secara terbuka di depan publik bila masyarakat memang sudah tidak menganggap seks sebagai hal yang suci dan secara ekskusif berlangsung di kamar tidur mereka yang sudah menikah? Namun bahkan dalam konteks sikap yang longgar tersebut, tetap ada materi-materi seks yang dikategorikan porno, dan itu dilarang.
Dampak. Pengalaman Amerika menunjukkan bahwa, pertama, pelarangan terhadap pornografi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kebebasan informasi. Kedua, definisi pornografi bukan tunggal dan sangat bergantung pada standard nilai masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sampai saat ini pun, ada penafsiran berbeda tentang pornografi antara negara bagian dan daerah di AS. Majalah seks //Hustler//, misalnya, tidak bisa ditemukan di beberapa daerah karena diangap sebagai barang terlarang, sementara terjual bebas di wilayah lain.
Tapi, kembali pertanyaannya: mengapa kecabulan tidak tergolong ke dalam wilayah yang dilindungi dalam gagasan kebebasan informasi? Ini berkaitan dengan soal ‘kepantasan’ dan ‘dampak’ dari materi yang tersaji di wilayah publik. Dalam hal kepantasan, materi cabul dapat disejajarkan dengan aktivitas ‘buang air kecil di tempat umum’. Anda tentu saja boleh buang air kecil, namun kalau Anda melakukannya secara terbuka di hadapan publik, Anda dapat dianggap mengganggu ketertiban umum. Begitu juga, Anda tentu saja boleh merekam aktivitas hubungan seks Anda di rumah dengan kamera video. Anda mungkin bisa meminjamkan rekamannya ke teman Anda. Tapi begitu Anda menyebarkannya ke wilayah publik masalahnya jadi lain.
Isu ‘dampak’ adalah soal apa yang diakibatkan media porno, baik dalam proses pembuatannya maupun terhadap mereka yang mengkonsumsinya. Kembali ke contoh AS, penyebaran materi hubungan seks melalui media memang dipercaya akan mendorong promiskuitas, namun itu kini dilegalkan karena masyarakat AS memang mengizinkan promoskuitas. Namun penggambaran seks dengan kekerasan yang eksesif dilarang karena, antara lain, dipercaya akan berdampak pada penyuburan kekerasan seksual. Begitu juga pornografi anak dilarang karena dia dipercaya, antara lain, akan menyuburkan bentuk-bentuk eksploitasi anak secara seksual.
Dalam hal ini, pornografi tidak bisa disejajarkan dengan babi, melainkan dengan obat bius. Konsumen tidak dibiarkan memilih antara membeli atau tidak membeli obat bius, karena dampak yang ditimbulkan penggunaannya, baik terhadap individu pemakai maupun masyarakat. Begitu juga dengan pornografi. Kaum pejuang hak-hak perempuan dan anak telah menyuarakan bagaimana pornografi bukan saja isinya melecehkan dan merendahkan harkat perempuan dan anak, tapi juga mendorong para konsumennya menjalankan perilaku seksual yang menindas, menghina, dan penuh kekerasan. Para agamawan, ahli kesehatan dan pendidik menyuarakan bagaimana pornografi menyuburkan perilaku seks tidak sehat yang, pada gilirannya, menyuburkan berbagai masalah sosial: AIDS, kehamilan remaja, aborsi, orangtua tunggal, perceraian, yang terutama dirasakan dampak terburuknya di kalangan menengah ke bawah. Para ahli komunikasi menyedikan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa segenap keprihatinan itu bukan sekadar kecemasan kosong semata.
Yang ingin ditunjukkan di sini ada cukup banyak alasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa pelarangan terhadap pornografi bukanlah pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan infromasi dan kebebasan individu untuk memilih. Di satu sisi, isunya adalah ‘kepantasan dan kesantunan’. Namun yang lebih penting lagi adalah apa yang ditimbulkan pornografi.
‘’Pornografi,’’ kata Angela Dorkin, ‘’adalah penghancuran tubuh dan jiwa perempuan’’.
Dorkin adalah seorang feminis, dan karena itu yang ia bicarakan ‘hanyalah’ perempuan. Namun bagi banyak pihak, yang dihancurkan pornografi jauh lebih luas dari itu: anak, pria, keluarga, masyarakat. Dan untuk alasan itu, terlalu hina rasanya untuk menyertakan kebebasan pornografi di dalam proses memperjuangkan kebebasan informasi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

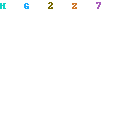
0 Response to "VCD Porno dan Kebebasan Memilih"
Posting Komentar