“Sudahlah, sholat mah sholat weh enggak usah ngajak-ngajak Abah. Da geus kolot abah mah!"
Aku, Iis dan Kang Nanang dibuat menganga. Bingung dengan penolakan rajukan yang kami lancarkan. Bahkan untuk sholat 'id yang hanya satu kali dalam setahun pun, Abah masih sulit diajak damai. Sempat Iis kehabisan akal menggolkan Abah untuk shalat Jumat. Mati-matian ia menge-rahkan energinya membujuk abah dengan se-gala keterbatasannya. Sehingga ia pernah me-ngancam, tidak akan memasak untuk Abah hari itu. Tapi Abah mudah saja berkelit, "Sehari tidak makan mah moal matak paeh ieuh!"
"Menikah lagi?!" suaraku meninggi. Tuntutan akademik, amanah sebagai aktivis, serta beban kerja paruh waktu di Daarut Tauhiid sudah lebih dahulu mengantri menuntut jalan keluar.
Kang Nanang memang belum tersentuh emosinya tentang ba-hasan ini. Aku yang tercatat sebagai ma-hasiswa Psikologi, walau belum sampai ilmunya, sedikit ba-nyak mengerti. Seti-daknya segala pesan Allah yang memposkanku di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI sangat dapat membayar kekecewaanku yang terjegal di FIKOM-UNPAD.
"Ingat, Kang Abah sudah menginjak kepala enam ," nadaku direndahkan. Untuk kondisi tertentu, sentuhan DT sanggup mele-burkan temparamenku.
"Apa yang salah dengan usia setengah baya lebih itu?!" gantian emosi kakakku satu-satunya ini meletup. Beradu cakap dengannya, me-ngajakku untuk sering-sering mengurut dada. Kuakui sebagai teknisi komputer di belakang layar, Kang Nanang terpergoki mengabaikan pengasahan sikap.
Aku terangkan tentang makna masa dewasa lanjut. Bahwa ia berkarakter senes-cence. Bahwa perkumpulan status kelompok minoritas menjadi pelarian. Bahwa pendapat sendiri tentang keadaan diri lebih disenangi. Bahwa pengurangan jumlah kegiatan mulai terjadi. Bahwa perasaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi muncul ke permukaan. Bahwa peluang mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan terbuka lebar. Bahwa keinginan menjadi muda kembali sangat kuat. Bahwa
"Jika begitu, Akang percayakan sepe-nuhnya padamu mengenai ini," walau pucuknya dapat melunak, namun entah dorongan meteri yang kang Nanang patok dirasa belum menggugah Abah. Di ujung pesawat sana salam menutup. Telepon gengamku segera kumasukkan ke saku bajuku.
***
"Abah membutuhkan teman bicara, A," suara Iis lembut meresap ceruk hatiku. Kian aku perhatikan, sosok Iis mendewasa bak sosok almarhumah Emak. "Jika kita bersedia proaktif dan menyingkirkan egoisme kita sebagai seorang anak Abah akan terpancing untuk membuka diri. Sebetulnya Abah enak diajak bicara, A "
"Tentang ibadah Abah yang menurun?" ulukutek leunca yang dipesan abah aku cicipi sepiring visin, "Kirang oncom, 'Is!"
"Faktor kedekatan yang kita bangun masih rapuh, 'A," perkataan adik bungsuku ini sanggup mengecilkan keberartianku sebagai mahasiswa Psikologi. Apalagi sentuhan lembut keibuan Emak sungguh menambal bolong abah. Sehingga ada kesan, Emak segalanya.
Emak memang sosok istimewa di mata Abah. Motivasi beribadah Abah pun berakar dari kesediannya sebagai pasangan hidup. Dan aku mengenang kegigihan emak menampilkan contoh istri solehah.
"Menyesuaikan diri dengan kematian pa-sangan hidup. Bukankah Aa yang mengatakan itu", kata Iis lagi.
"Iya, tapi tidak lantas sumbu ibadahnya pun mati, bukan?" kejarku "Itu tugas kita. Menyulutnya dengan api komunikasi "
***
"Kumaha abah damang?" Sapaku hangat. Kontak jarak jauh Bandung-Subang di-tanggapinya dengan dingin.
"Bah betapa nyamannya tukang parkir. Ketika dititipi mobil ia tidak pernah merasa memiliki. Ketika diambilnya pun, tidak pernah sakit hati " sindirku mengulang pernyataan Aa Gym. Barangkali siraman sejuk ini dapat menyembuhkan luka ditinggalkan orang yang dicintainya. Abah lebih banyak mendengarkan pasif. Tiada sahutan antusias sebagaimana wajarnya seorang bapak. Tiada perhatian layaknya seorang ayah. Tiada wejangan tulus seperti halnya pemimpin keluarga. Maaf, bukan berarti menuntut.
Terus terang pola pendidikan yang beliau terapkan kepada kami malah menciptakan kekurang akraban. Abah keras. Pikirnya; kontak fisik, bentakan, dan cara kasar lain layak kami terima sebagai bekal hidup. Dalihnya, de-ngan tanpa maksud meremehkan, klise: "Kehidupan di luar keras 'Jang!" begitu panggilan sayang kepadaku: 'Ujang'. Panggilan yang mampu membangunkan kesadar-anku bahwa aku adalah buah hatinya.
Bahkan ketika aku mesti me-ngorbankan akhir pekanku lantaran ter-bentur shift ker-ja, demi untuk menengok abah; aku di anggap bak angin lalu. Mataku tidak dapat di tipu, jika tangan beranjak mengeriput itu mengupas apel merah, buah pir, atau mengunyah anggur hijau, hanya kompensasi dari kehadiranku saja. Begitupun, bila setelah aku persiapkan secara matang bahan obrolan yang sesuai minatnya, namun ujungnya Abah beralih ke Televisi 21 Inchi di depannya; itu hanya pe-ngalihan pembicaraan saja. Sama tanggapannya ketika pagi buta aku mem-beranikan diri mengajaknya ke pasar untuk mencari panganan kesukaannya: dongkal, gonjing, goreng getas, dan atau gemblong Abah lebih memilih meringkuk di balik sarung tipisnya. Alasannya, sembari menunggu surabi yang dibeli Iis di ujung gang sana. Padahal kami tahu benar, kue basah dari beras itu bukan jajanan prioritasnya.
Puncaknya, tatkala ketidak bermaknaan akan segala keberadaanku di sisinya terpancar dan aku pun memuntahkan segala keganjalan yang terserak; emosiku membuncah hingga ubun-ubun, "Abah egois!"
Kerongkonganku tersekat parau, "keras kepala ," dadaku sesak. Belum terpikirkan jika sejuta ampun harus aku panjatkan di ujung penyesalan kelak.
"Terima kasih telah mengiris hati kerdil Abah ," aku terperangah menangkap nada datar Abah ini! Mataku panas. Gengsiku telah menyeretku untuk enggan bersimpuh di tubuh ringkihnya.
Pintu dibanting. Pertahanan mataku jebol. Perih nian bulir hangat ini memancar. Hati jeriku tidak tahan diremas egoku sebagai sesama lelaki. Saat sayup-sayup dengan suara basah Abah mengungkapkan rasa kebapakannya.
"Abah mencintaimu, 'Jang "
***
"Selamat ulang tahun, Abah !" kataku. Tirai kamar tersibak. Hari ini Abah tepat berusia 65 tahun. Hening yang menyambut.
"Sanes 'Selamat ulang tahun'. Tapi, 'Selamat hilang tahun'!" ujar Abah serius sembari melipat sajadah. Aku terperangah. Sajadah ?! Pekikku dalam hati. "Eh, 'Jang, ari Rasululullah teh yuswana ngan 65 tahun, nya?!"
Ada panas yang menggelayut di mataku. Ingin rasanya aku segera meraih dan memeluk Abah.
(Kepada segala cinta sederhana ananda akan sejuta kasih untuk peluh yang menetes dan tenaga yang terperas kasar dari ayahanda dan ibunda di bumi-Nya).
Keterangan :
Weh : Saja;
Da geus kolot ieuh abah mah: Abah sudah tua, kok ;
Moal matak paeh ieuh: tidak akan mati, kok ;
Senescence(Istilah Psikologi) : masa proses menjadi tua ;
kirang: kurang ;
kumaha damang Abah: bagaimana kabarnya Abah ;
Sanes: Bukan ;
Ari: kalau ;
Yuswana: Usianya ;
Ngan: hanya
[MQMedia.com]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

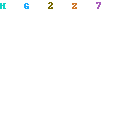
0 Response to "BAIT SENDU ABAH"
Posting Komentar