oleh : Nataresmi Salinggih
Mengapa? Kernyitan samar mengiringi saat hatinya bertanya demikian. Dengan mata memicing ke arah matahari, ia berkesimpulan senja segera tiba. Saatnya mandi sore, dan mencari makanan di kulkas buat teman nonton. Tapi ia tahu sudah kehilangan waktu untuk kebahagiaan yang sederhana itu.
Dunia makin bermasalah dan kehidupan akan menunjukkan ketakadilannya kalau terlalu banyak bertanya. Untuk sesaat ia halau pikirannya dan memusatkan mata pada lalu-lalang orang di peron stasiun. Yang datang dan pergi tergesa-gesa, keluarga dengan anak-anak yang berceloteh serta tas tas bawaan, atau berpasang-pasang kekasih yang menikmati detik per detik menjelang perpisahan mereka. Tukang koran. Pedagang makanan minuman. Lengking peluit dan mesin kereta bersuara bising.
Kesibukan rutin. Mendadak terasa ganjil setelah matanya menyambar langit dan menenggelamkannya pada kebiruan tanpa batas. Benaknya terusik tanya: apakah kesibukan manusia di kulit bumi terasing sendirian, di jagat mahaluas berdiameter 100 parsec ini?! Dari milyaran bintang belum diketahui apakah kehidupan di bumi berkawan. Kalau tak ada, alangkah lengangnya jagat.
Hal-hal astronomis mengingatkannya pada kuliahnya yang berantakan di pertengahan semester kelima ini. Observatorium Bosscha dan bougenville tuanya yang setia memunculkan bunga tiap musim penghujan, apalagi saat purnama sepanjang Mei-Oktober waktu diadakannya Malam Umum, tinggal sepotong kenangan belaka. Betapa, ia lebih tertarik untuk merekam alam yang puitis itu kedalam sekian bait puisi daripada mengutak-atik teropong Zeiss untuk memperoleh setumpuk hasil mengamatan.
Aku terperangkap di jalan yang seharusnya bukan untukku, gumamnya. Mengapa? Seperti biasa, ia tak mendapat jawaban. Dicobanya menerka, mungkin karena ketertarikannya pada sastra. Atau, keraguannya terhadap prospektif ilmu murni menjamin masa depan, seperti rata-rata temannya. Atau juga, konsep pengetahuan eksak yang sulit ia pahami. Ia tak menemukan jawaban. Tapi tangannya menemukan setumpuk kertas di saku jaketnya. Surat. Kartu. Foto kawan Astronomi Angkatan 97 berlatar gerbang Ganesha.
“Tetep semangat. Semoga Nobel impianmu tercapai, Penyair! Dengan cinta, kawanmu: Nataresmi” (Ada gambar bibir bertuliskan Cup! Dekat tanda tangannya).
“Dari Ina: Pergi saja, dirimu pergi....bilang saja pada dunia... Ah, Ul... gua “gak bisa meneruskannya. Jaga diri baik-baik ya!” (Ia tersenyum kecut membayangkan Ina berlagu Krisdayanti dengan sok melankolis).
“Ul, ingat tidak waktu kita sekelas hiking ke Maribaya? Saat aku hampir tergelincir dari jembatan, kamu menyelamatkanku. Kalau tidak, mungkin aku terseret pusaran air terjun. Lewatmu, aku masih diberi-Nya umur. Terima kasih ya, Ul, untuk semua kebaikanmu. Semoga Allah tetap bersamamu. Salam, Neflia. (Ah, Li...bukannya aku yang sering merepotkanmu. Minjem duitlah, maksa ditraktir, nyontek PR...).
Sudut matanya memanas. Kartu-kartu perpisahan dibacanya satu per satu.
“You”re the best my friend. Be carefull “n wish your dream come true. Vivi. (Pesan singkat ini mengingatkannya kepada sosok Ambon yang keranjingan komputer: Avivah.)
“Sok didoakeun sing pinter, bageur, cageur. Jangan lupain gue. And Missisipi is mighty, but it starting at Minnesota at a place where”d you could walk, cross with five step down.
Sampai ketemu lagi nanti. Saya sudah beranak empat dan punya Land Rover dan jadi desainer terkenal. Si Idola tea: Maria M. Lubis. (Bibirnya membuat garis tawa. Si Lurus ngaku - ngaku peranakan Batak-Spanyol tapi sangat Sunda ini temannya bercanda. Mereka mengangankan punya sekolah alam yang tidak menjejali muridnya dengan hafalan. Masihkah ada waktu buat mewujudkannya? Ia menggeleng).
“Je suis triste. Kita kehilangan nih, Ul. Ul yang manis dan misterius. Eh, dulu aku berhutang 2.000 perak bekas jajan soto, ikhlaskan ya!!! He ... he...”
Tya si Nona Prancis, Mariyam, Ichal, Zaid, Ketut, Udin, Farkhan, Yana, saling tersenyum di foto itu. Ia tatapi dengan pandangan mengabur.
Hey, mengapa menangis? Meski percaya airmata bukanlah perwakilan emosi sesungguhnya, ia saat ini ingin melakukannya selagi pikirannya memaklumi kesedihan yang timbul kali ini. Sebab telah lama ia menahan karena keyakinan bahwa Tuhan akan memberinya kekuatan kalau ia tabah dan tidak menangis.
Saat Papa tertembus peluru nyasar dalam huru-hara politik di penghujung Mei 1998, rasa kehilangan itu ia bunuh dengan susah payah. Bukankah mati; kapan, di manapun dan bagaimanapun, kembalinya ke tempat yang sama. Saat harga kostnya makin menurun dan akhirnya hanya sebuah kamar pengap di pojok Tamansari Bawah yang mampu ditinggalinya, ia belum menyerah. Pun pada kemampuannya yang sedang-sedang dalam menghadapi rumitnya mata kuliah Fisika, ia coba bertahan. Meski akhirnya kebakaran juga. Dua D, satu E, dua C, dan A sendiri. Melarikan diri ke Perpustakaan Salman, bau kertas dari novel tua menjadi karibnya. Salah satu favoritnya karya Jose Rizal Noli me Tangere yang gelap dan puitis.
Pertahanan yang telah dibangun dari retak-retak kekuatannya memang tidak kokoh. Mama berkunjung. Bercerita tentang Josh, insinyur lulusan Delft. Sudah mapan. Putra bungsu karib Papa. Saat itu ia menyelami mata Mama dalam-dalam. Ditemukannya di situ ketiga adik lelakinya mencari masa depan. Tanpa kata, semata karena niat baik, ia iyakan permintaan ibunya. Ia memararelkan cintanya kepada Josh karena mencintai ibu dan adiknya. Juga deretan nilai ujiannya yang pas-pasan menjadi pertimbangan lain. Tetapi ia menyodorkan alasan berbeda kepada teman-temannya saat berpamitan; ingin serius menulis mungkin kelak mengambil jurusan sastra.
Paling nanti Maria atau siapa pun akan memergokinya sebagai nyonya belia, ia tersenyum getir. Dan untuk itu ia menyiapkan sebuah gurauan klise; ternyata menikah itu enaknya cuma 30 %, yang 70 % itu enak sekali. Haha, ia nyaris tertawa. Josh, samar-samar benaknya merekonstruksi sosok bungsu yang manja, montok dan atraktif sebagai kawan sekilas masa kecil. Keajaiban alam yang berlangsung perlahan, seiring waktu mengubah setiap benda dalam keteraturan yang harmonis. Pun dengan Josh. Dia legam dan langsing seperti patung-patung dewa Yunani. Perhatian dan religius. Apapun dia dan bagaimana, satu saja pertanyaan mengusik benak: bisakah ia rela terhadap dirinya sendiri yang tiba-tiba saja dihampiri kehidupan baru, sebagai istri dan kehilangan dunia mahasiswa begitu saja!
Tuhan!! Aku tak mengenal-Mu terlalu baik, desisnya, hanya berbekal kesadaran kecil tentang satu hal: seorang manusia selalu dalam ujian, yang menjadi benang merah hubungan kita. Dan maaf, benang itu sekarang tampak teregang dengan jalinannya sebagian pecah menahan beban ini...
Tap. Tap. Tap.
Tepukan berulang mampir di bahunya ia mengangkat muka segera.
“Meski tidak terdengar, saya dapat menerka seberapa dalam kesedihan Anda. Perlu tissue-kah?”
Ia mengabaikan tawaran ramah itu dengan gelengan lemah. Dijepitnya hidung sekilas, muncul suara ingus yang terhisap tarikan napas, terasa panas dan berair, ia bisa menerka kekontrasan antara warna merah di hidungnya dengan kulitnya yang putih pucat.
“Hendak ke mana?”
“Surabaya,” ujarnya mengambang. Minggu depan aku menikah, lanjut batinnya. Sejurus kemudian ia balik bertanya, “dan Mbak?”
Orang itu tertawa kecil, menganguk-angguk. Aneh, gerutunya. Tetapi wajah sedemikian ramah itu mengirimkan perasaan ditemani yang menenteramkan.
“Anda nampak lapar. Saya kebetulan punya makanan.” Orang itu membuka travel bag-nya, mengeluarkan kotak berisi kue pisang keju khas Stasiun Bandung “Kartika Sari”. Menyodorkan tepat di depan matanya, dan meski agak sungkan ia mengambil satu. Usai berterima kasih, langsung dikunyahnya, setengah malu ia lantas menyadari sikapnya agak bernapas.
“Bismillahirrahmanirrahim,” ucap orang itu keras-keras.
Seketika ia tersedak. Menoleh heran dan menemukan ekspresi yang datar saja. Seperti diingatkan ia pun dalam hati mengeja basmallah.
“Hmm. Enak ya. Saya juga suka makanan Bandung yang lain: siomay dan es cendol.” Gayanya bercerita seolah mereka sudah akrab lama. “Cuaca di sini juga nyaman, dan gampang mencapai tempat buat berwisata alam yang dekat kota. Pernah ke Hutan Jayagiri?”
Ia mengangguk. “Juga mendaki Gunung Burangrang, keliling kawah Tangkuban Perahu dan jalan kaki selama sembilan jam ke Situ Lembang. Waktu berkemah di Rancaupas saya malah pernah terjebak badai dalam suhu 5 derajat Celsius...” paparnya dengan suara rawan. Petualangan alam sudah selesai baginya.
“Wow. Menyenangkan, bukan. Saya harus bersyukur dengan semua pengalaman pengalaman yang menarik, karena...,” orang itu menunjuk para pekerja yang sedang membersihkan badan kereta, “saya tak yakin mereka punya waktu untuk menikmati hal serupa kita. Paling sekedar menginginkan. Tapi hidup jadi tak seimbang kalau selalu memuaskan keinginan, akan seperti menguras air di laut. Tak kunjung habis. Tuntas satu keinginan saya akan segera tahu keinginan berikutnya jumlahnya sudah berganda. Tetapi, tanpa itu... uh, alangkah membosankan.” Orang itu terkekeh halus.
Ia menggumam tak jelas sebagai komentar. Dengan bosan dilayangkannya mata ke kejauhan cakrawala yang dilukisi cahaya lembayung. Dalam ujian Laboratorim Astronomi, ia pernah menemukan soal: mengapa pada siang hari langit berwarna biru sedangkan sore hari lebih kuning? Jawabannya ketika itu: saat mengelilingi matahari bumi yang bulat juga berotasi terhadap sumbunya, suatu tempat akan mengalami perpindahan sejauh seperempat keliling lingkaran bumi selama rotasi 6 jam, hal itu mengakibatkan perbedaan panjang jarak ke matahari. Kala siang hanya gelombang cahaya biru yang terhambur di udara, dan pada sore hari yang jaraknya lebih panjang menyebabkan gelombang cahaya kuninglah yang tertangkap mata pengamat di bumi. Tetapi ia lebih suka mendefinisikan cahaya kuning senja hari itu sebagai lukisan naturalis yang membangkitkan rasa sentimentil. Seperti waktu ini, setelah salam perpisahannya dengan Kampus Ganesha, Perpustakaan Salman, kawan-kawannya, dan masa lajang! Ketika rasa kehilangan mendekat pasti, betapa tersadari keterikatan yang ketat dan tak hendak melepasnya dari takdir kita. Tetapi, hidup terus berjalan.
Ia bangkit menepuk-nepuk debu yang tak ada pada jinsnya. “Saya salat Maghrib dulu.”
“Silakan. Saya tidak karena... biasa perempuan,” Orang itu mengibaskan tangan dan tersenyum. “Anda lagi sedih. Mengadulah saat salat. Pasti Anda diberi-Nya kekuatan. Percaya, bukan?!” Matanya teduh sekali.
“Bisakah saya titip tas dan koper ini kepada Anda?”
Orang itu mengiyakan. Mengisyaratkan keamanan terjamin. Setelah berterima kasih, ia menuju pintu keluar peron. Berdesakan mengambil wudhu. Musala di ujung barat stasiun terlalu kecil untuk menampung jamaah. Lebih seperempat jam baru mendapat giliran, setelah orang agak lengang. Didapatinya masbuk pada takhiyat awal, lalu menyelesaikan kedua rakaat terakhir dengan perasaaan abstrak tanpa kontur. Seolah dipeluk ke dalaman Mahagaib yang mengisi seluruh sel dan syarafnya. Dari ucap ke ucap, gerak demi gerak. Hanya bacaan sepanjang salatlah bahasa Arab yang dimengertinya. Dan ia bersunguh-sungguh kali ini. Maka kelegaan tanpa batas saat menyudahi dengan salam, memaku keyakinan di dadanya: mengalirnya air tenang adalah kepasrahan yang mempunyai kekuatan seperti gelora laut. Detik berikutnya ia berdoa agar diberi-Nya sifat air, setia meliuk sepanjang arus dan mengikis satu per satu perintang. Di belokan pertama telah menungguinya seorang Josh. Ia percaya, seseorang tidak akan dibebani melebihi kesanggupannya.
Ia hembuskan napas. Ia menyadari kelegaan yang tiba-tiba. Ia merasa kesejukan.
Dunia nyata menepuknya dan memberi tahu waktu sudah pukul setengah tujuh. Agak bergegas dimasukinya peron dan ia terkesiap menumbuk bangku yang didudukinya tadi. Detak sepatunya seperti berlomba tiba. Ke mana orang tadi?!
Barang-barangnya utuh. Rasa bersalah menyeruak, telah berburuk sangka sebelumnya. Memberesi bawaan pun, kepalanya sibuk bertanya-tanya. Akhirnya, ia mendekati seseorang.
“Maaf, apakah saudara melihat seseorang tadi duduk di sini pergi?”
“Anda bercanda? Tak ada siapa-siapa, bukan? Sedari tadi Anda duduk sendirian dan terlihat sedih.”
Ia mengabaikan keheranan orang itu. Malaikat? Simpulnya menjawab sendiri. Tapi dia perempuan, ralatnya, tentu makhluk gaib yang baik hati. Yang tadi itu begitu nyata. Kartika Sari dan tatap matanya. Tiba-tiba sel otaknya mengolah informasi tak masuk akal menjadi hal terlogis, mendatangkan kejutan di ujung-ujung syaraf membuat kulitnya menebal tanpa rasa, seperti dibius. Merinding dingin.
“Aku ditemani,” gumamnya dengan perasaan nyaman.
“Kereta Turangga dengan tujuan Surabaya akan diberangkatkan tepat pukul tujuh malam, telah disediakan di jalur tiga. Kepada para penumpang yang telah memiliki karcis silakan segera naik.” Pengumuman dari pengeras suara.
Bandung, selamat tinggal.
Kakinya menuntun ke selatan. Melewati tempat sampah, ia berhenti, mengambil kertas-kertas dari saku jaketnya dan membuangnya. Satu episode hidupnya telah selesai. Kusimpan saja kalian dalam hati, batinnya. Sayang, ia melewatkan secarik kartu putih yang belum dibacanya. Dari Nataresmi. Sebait syair karya Sufi dari Konya, Rumi:
Pergilah ke pangkuan Tuhan, dan Tuhan akan memelukmu
dan menciummu, dan menunjukkan
bahwa Ia tidak akan membiarkanmu lari dari-Nya
Ia akan menyimpan hatimu dalam hati-Nya,
siang dan malam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

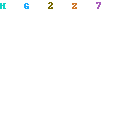
0 Response to "SEPOTONG KENANGAN UL"
Posting Komentar