Siang belum terlalu panas. Saya lirik jam tangan. Pukul sembilan kurang sedikit. Kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ‘Veteran’ yang baru saya masuki lengang. Tidak banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang terlihat berlalu lalang. Saya terpana melihat banyaknya gedung yang tinggi menjulang. Di mana gedung pasca sarjana fakultas ekonomi? Kata panitia, acara akan mulai jam 9. Saya hampir terlambat. Padahal sebenarnya, kalau bisa saya ingin tiba di sana sebelum dua pembicara yang lain, agar punya bahan untuk menyiapkan mental dan bahan pembicaraan. Saya memang ingin belajar disiplin, menghargai waktu, meski sampai sekarang belum kunjung berhasil.
Dengan ransel yang tergendong di pundak, saya terus melangkah. Karena bingung, maka saya berinisiatif bertanya kepada satpam yang berada di pos jaga. Setelah mendapat jawaban, saya pun melangkah lagi. Sepi, tak ada banyak mahasiswa maupun mahasiswi. Tapi, ada yang cukup menarik dalam pandangan mata saya. Lambaian umbul-umbul merek rokok ternama yang berdiri tegak di sepanjang lapangan rumput yang luas. Di tengah, ada sebuah panggung megah dengan alat musik yang besar-besar. Ada dua tenda kecil di dekat panggung itu.
Musik. Rokok. Saya tiba-tiba resah. Meski demikian saya terus melangkah. Berjalan sambil celingak-celinguk, di sepanjang jalan yang saya lewati suasananya tak jauh beda. Sepi. Ternyata, sesampai gedung pasca sarjana juga sama. Sepi. Hanya ada beberapa gelintir orang yang berlalu-lalang. Sejenak ragu menyergap. Acaranya jadi atau tidak?
Seorang mahasiswa, dengan langkah tergesa, datang menghampiri, “Mbak Jazimah Al-Muhyi?†Saya mengangguk. “Acaranya di sini, Mbak.†Mahasiswa tadi membuka pintu sebuah ruangan. Sebuah ruang kuliah yang menurut saya cukup mewah. Ruangan ber-AC dengan kursi empuk yang bisa berputar. Maklum, ruang kuliahnya mahasiswa S-2, yang tentu saja membayar lebih mahal ketimbang mahasiswa S-1. Tak masalah, selagi bisa berfungsi maksimal. Biar belajar lebih nyaman dan konsentrasi.
Melihat tempat acaranya, sejenak saya termangu. Acara bedah buku di ruang kuliah? Saya perkirakan kursi yang ada di situ hanya sekitar 30. Jadi, panitia sudah pesimis kalau pesertanya maksimal 30? Daripada bodoh berkelanjutan, saya memilih bertanya, “Kampus ini kok sepi sekali. Ke mana para mahasiswa?†“Ini kan hari Sabtu, Mbak. Memang selalu begini.â€
Ops, saya pun menepuk jidat (meski imajinasi). Saya jadi ingat semasa masih kuliah. Mahasiswa-kebanyakan-memang suka protes kalau ada dosen yang di hari Sabtu masih saja memberi kuliah. Jadinya, jam kuliah yang jatuh pada hari Sabtu seringkali digabung dengan hari lain. Kalau dosen sibuk alias punya jam terbang super tinggi, akibatnya sering kosong. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Asal dosen tidak pelit memberi nilai, biasanya dia tetap menjadi dosen favorit pilihan mahasiswa (malas).
Beberapa menit menunggu, satu demi satu orang datang. Kayaknya sih panitia. Ngobrol sana-sini, beberapa di antaranya minta maaf karena molornya acara. Saya mengangguk saja. Sudah biasa. Sedikit ngobrol, saya bisa menyimpulkan kalau panitia memang tak mematok target adanya peserta yang banyak karena Sakti Arisena, gitaris S07 yang semula dijadwalkan, tak bisa hadir. Begitu pula Icha Jikustik tak bisa menggantikan. Maklum, Sabtu adalah hari sibuk bagi para pemusik, setahu saya begitu. Menyiapkan konser untuk malam minggu tentu butuh persiapan fisik yang prima.
Mundur sekitar satu jam, acara pun mulai. Lumayan meriah. Apalagi Dr. Nurhadi begitu detail dan menarik menyampaikan analisanya terhadap buku yang dibedah. Saya lebih banyak berbicara soal proses kreatif. Hadirin (yang pastinya tidak sampai 30) itu antusias bertanya. Alhamdulillah. Acara usai, seorang mahasiswi yang tampaknya panitia acara menawarkan diri untuk mengantarkan saya pulang. “Oke, kamu boncengkan aku sampai depan kampus saja. Biar aku naik angkutan umum.†“Kenapa, Mbak?â€
“Aku lagi flu. Naik angkutan umum aja, biar gak banyak kemasukan debu. Lagipula, sini-Jombor kan jauh.†Dia setuju.
Motor berjalan, saya sampai lagi pada pemandangan itu. Umbul-umbul merek rokok yang berkibar-kibar dan sebuah panggung megah berisi alat-alat musik besar. Sampai keluar dari gerbang kampus, saya masih menatap pemandangan itu. “Kampus. Musik, rokok ....†saya mulai bergumam. “Di sini sering banget ada acara begini, Mbak.†Mahasiswi itu memberi keterangan. Dari nada bicaranya, saya tangkap rasa kecewa. Sebuah rasa yang juga menghuni hati saya.
Siang itu, saya merasa pilu. Terlebih saya teringat berbagai bedah buku maupun diskusi yang pernah saya ikuti. Seramai apa pun, tetap tak mampu menyaingi kemeriahan sebuah konser musik. Menyaksikan kemeriahan persiapan konser musik yang terhampar di lapangan rumput nan hijau, di depan deretan gedung megah kampus se-ternama UPN, membandingkannya dengan acara bedah buku yang baru saja berlangsung di sebuah ruang kuliah, saya merasakan suatu hal yang kontradiktif. Sebuah bedah buku, buku yang ditulis oleh seorang mahasiswa UPN, ‘disembunyikan’ di sebuah ruangan kecil berkapasitas kurang lebih 30 orang saja. (Padahal, berapa persen jumlah mahasiswa yang telah menghasilkan buku? Tidakkah itu adalah sebuah prestasi yang patut dihargai?)
Saya tatap lagi panggung dan umbul-umbul yang meriah itu. Resah itu tak saya biarkan menjelma menjadi energi negatif yang pastinya akan menghancurkan. Resah itu, saya olah menjadi harapan. Sebuah mimpi. Kekuatan mimpi, saya meyakini kedahsyatannya
“Saya punya mimpi, Dik. Suatu saat, di lapangan rumput yang luas itu akan terdapat panggung yang berisi buku-buku. Di sana ada bedah buku, diskusi buku, seminar ilmiah. Karena ini kampus. Karena di sini tempat para intelektual harapan bangsa berada.â€
Mahasiswi itu memberikan sorot mata penuh harapan. Saya lega. Saya tahu mimpi itu akan melibatkan banyak sekali tangan yang harus bekerja keras. Budaya cinta membaca, budaya cinta menulis, budaya cinta berpikir, budaya cinta mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa ... bukan perkara mudah untuk menumbuhkembangkannya. Banyak pihak harus terlibat secara serius. Hedonisme, kapitalisme. materialisme, instan-isme bahkan kanibalisme telah teramat kuat mencengkeram hidup mayoritas penduduk negeri ini.
Angkutan umum yang saya tunggu sudah nampak di kejauhan. Saya tahu harus segera pulang. Ada tugas lain menanti di rumah. Saya tepuk pundak mahasiswi yang baik itu sembari berkata, “Dik, padamu kutitipkan mimpiku.â€
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

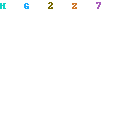
0 Response to "Padamu Kutitipkan Mimpiku"
Posting Komentar