Tiga puluh tahun lalu, lulus sekolah, yang namanya wisuda, hanya berlaku bagi perguruan tinggi, lulusan setingkat sarjana. Keluaran SD, SMP, SMU cukup puas dengan Selamatan Jenang Abang, home-made. Ibu buat sendiri kue-kue di rumah, jika anak-anaknya naik kelas atau lulus sekolah, sebagai wujud syukur ke hadirat Allah Ta’ala, atas segala prestasi yang telah diraih anak-anaknya. Kue-kue ini dibagikan ke tetangga sebelah dan sanak-saudara.
Saya sendiri tidak pernah merasakan ‘nikmatnya’ mengenakan toga, kecuali setelah mengenyam perguruan tinggi. Tapi, di mana sih sebenarnya kenikmatan hakiki mengenakan toga dan pakaian kebesaran wisuda?
Sejujurnya, saya tidak mengerti. Makanya, ketika keponakan saya wisuda beberapa waktu yang lalu, sementara dia sibuk sekali bangun pagi dan kemas-kemas dengan aneka macam persiapan wisuda, saya cenderung kurang peduli. Saya tidak bisa menutupi diri sendiri, bahwa wisuda semacam ini tidak nampak hikmahnya, kecuali ‘sia-sia’.
Sia-sia. Karena sebelum wisuda, orangtua repot sekali mencari duit Rp 700 ribu untuk membayar keperluan wisuda. Itu besarnya ongkos wisuda untuk perguruan tinggi kelas kabupaten. Kalau saya rinci, bisa meliputi bayaran orang penting yang mewisuda, panitia, konsumsi wisudawan dan undangan, sewa gedung, meja-kursi, dokumentasi dan administrasi. Belum terhitung transportasi!
Banyak sekali? Memang! Namanya juga wisuda. Apalagi untuk tingkatan perguruan tinggi terkenal. Makin bergengsi nama perguruan tingginya, semakin mahal biaya wisudanya. Padahal, sesudah wisuda, apa yang mereka butuhkan, kerja kan?
Bulan-bulan ini banyak sekolah dan perguruan tinggi yang sibuk dengan aneka ragam wisuda. Keponakan saya terlihat senangnya bukan main! “Om, potret ya?†ungkapnya, minta difoto. Tukang rias pun harus datang pagi-pagi hanya untuk urusan sanggul dan jarit. ‘Sudah begitu aturan dari fakultas’, katanya. Belum lagi mencocokkan model dan warna sepatu dengan pakaian yang dikenakan.
Pokoknya: wah!
Sesudah itu, jemputan mobil sewaan datang. Berangkat ramai-ramai! Bapak, ibu, adik, calon suami kalau perlu, dan wisudawati itu sendiri. Semua ikut. Jumlah lulusan 300, yang hadir 3000 orang. Hari itu, benar-benar istimewa.
Di tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK), tidak kalah serunya! Jalan desa macet hanya karena anak-anak TK mau wisuda. Orangtua disibukkan dengan acara wisuda yang biar kecil-kecilan, urusannya makin ruwet. Mulai dari sepatu, pakaian, makanan kecil, hingga pampers.
Bagi yang kaya, agar lengkap dokumentasi wisudanya, menyewa studio untuk bikin ‘film’ dan di-VCD-kan. Yang nggak mampu, tukang foto amatiran sudah lebih dari cukup. Kalau perlu di-‘klik’ sebelum berangkat.
Akan dikemanakan anak-anak ini sebenarnya?
Acara wisuda, pemberian gelar: ahli madya, sarjana, pasca sarjana, SPd, ST, Dr , DR, Prof, dan lain-lain, sebenarnya untuk apa? Kalau hanya ingin memberikan penghargaan kepada seseorang sesudah dianggap mampu menguasai ilmu tertentu dan pada waktu tertentu, toh Imam Syafi’i misalnya, yang hafal al-Qur'an pada umur 9 tahun, tanpa gelar apa-apa, tanpa penghargaan apa-apa, namanya juga bisa besar.
Imam Bukhari yang ‘membabat’ 9000 hadits di luar kepala, juga memiliki nama gemilang dan harum, tanpa embel-embel doktor atau profesor. Padahal ilmu cendekiawan muslim itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Kajian ilmu mereka bukan hanya sebatas demi kepentingan duniawi. Ilmu mereka menembus kebutuhan manusia hingga hidup sesudah mati. Subhanallah!
Pak Arif dan Pak Zais di kampung kami puluhan tahun sudah menjadi tukang cukur rambut tanpa sekolah. Tapi mereka ahli di bidangnya. Dihargai oleh masyarakat. Berpenghasilan pula. Sementara, yang lulusan sarjana saja sekarang ini banyak yang nganggur.
Atau, Mbak Sri yang hanya berprofesi sebagai tukang pijet. Hampir setiap sore dia dipanggil oleh orang-orang yang butuh sentuhan tangannya untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Padahal, sekolah menengah pertama saja dia tidak lengkap.
Jadi, apa artinya pendidikan panjang, bertahun-tahun, formal, penuh teori, dan ditutup dengan pemberian toga, kalau kenyataanya produknya sebagian besar justru ‘kalah’ dengan seorang tukang cukur semacam Pak Arif, atau tukang pijat kayak Mbak Sri?
Pada zaman modern ini, kita telah dicetak untuk membentuk manusia yang menomor-satukan kebutuhan pribadi. Sejak kecil kita sudah mulai terbiasa dididik untuk mementingkan diri sendiri, alias egois. Mementingkan diri sendiri ini dikedepankan oleh sekolah-sekolah kita. Sehingga lulus sekolah seakan-akan identik dengan prestasi, gengsi dan kepentingan diri.
Anak-anak yang lulus sekolah tidak dibiasakan berkonsep, bahwa sekolah sebenarnya hanyalah bagian dari proses belajar yang tidak ada akhirnya. Sekolah-sekolah umumnya mengumbar jutaan janji, bahwa dengan sekolah, mereka bisa ini, itu; memiliki kompetensi ini dan itu, serta segudang sebutan profesi lainnya.
Padahal, di luar gedung sekolah sana, tenaga terampil tak terhitung jumlahnya. Tukang kayu, tukang batu, tukang gergaji, tukang gali, dan sebagainya. Mereka hanya kita sebut: ‘tukang’. Padahal, mereka adalah pasukan yang berdiri di garis terdepan dalam pembangunan rumah dan gedung-gedung, proyek perkantoran, hingga dam-dam pembangkit listrik. Merekalah mestinya yang menyandang insinyur sejati.
Mas Gatot, tetangga sebelah kami, hanya lulusan SD. Setiap hari, orang antri meminta tenaganya, memperbaiki kerusakan listrik dari rumah-ke rumah. Rekan saya, lulusan Elektro ITB, malah jadi budayawan. Biar keren kedengarannya kan?
Tanpa sekolah formalpun, tukang-tukang ini ternyata bisa juga hidup. Dalam arti, mereka bisa jadi ‘manusia’, tumbuh, bekerja, dan berkembang, tanpa harus duduk di bangku sekolah. Itu bukan berarti, bahwa pendidikan di sekolah formal tidak penting. Karena di sekolah yang formallah terdapat laboratorium, perpustakaan dan tenaga-tenaga ahli yang bersertifikat.
Namun demikian, orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal ini, bisa juga langsung praktek ke ‘laboratorium terbuka’. Mereka juga bisa mengunjungi ‘perpustakaan hidup’, serta ‘Kuliah Kerja Nyata’ tanpa batas. Mereka tidak butuh sekolah tinggi maupun universitas yang biaya wisudanya bikin bulu kuduk berdiri, untuk mencetak agar mereka jadi manusia yang berguna.
Wisuda dengan segala macam acara ‘ritual’nya, hanyalah satu contoh, betapa kita ini secara sistematik sudah dicetak sebagai manusia-manusia yang belajar mementingkan diri sendiri.
Apakah tidak dikatakan mementingkan diri sendiri, bilamana sesudah wisuda dan menyandang gelar tertentu, lantas kita berani ‘mematok’ harga, berapa seharusnya kita dibayar? Apakah tidak mementingkan diri sendiri namanya, bila sesudah wisuda, kita hanya mau bekerja kalau sesuai selera? Apakah tidak mementingkan diri sendiri namanya, bila sesudah wisuda, tidak mau kerja, karena terlalu berat tantangannya?
Lihatlah orang-orang desa yang serba bisa! Mencangkul di sawa, memanjat pohon kelapa, merawat tanaman di ladang, mengolah kayu untuk jadi bahan bangunan, mencari batu kerikil di sungai, membakar batu bata, menganyam bambu, hingga membangun rumah. Mereka memiliki segudang ilmu dan ketrampilan tanpa gantungan selembar sertifikat pun di ruang tamu mereka.
Mementingkan diri sendiri, egois, atau selfish, berarti meletakkan kepentingan diri sendiri diatas kepentingan orang lain. Di dalam Islam, mementingkan diri sendiri itu bertentangan dengan ajarannya. Hal itu terlihat dari sholat saja misalnya, kita dianjurkan berjamaah. Dengan berjamaah, terkandung nilai-nilai kebersamaan umat. Ringan sama dizinjing, berat sama dipikul.
Sesudah sholat, kalau mau, orang-orang bisa menyelesaikan banyak persolan hidup di dalam masjid. Sedangkan jika sholat sendiri-sendiri, siapa yang bakal membantu kita menyelesaikan masalah, dengan tinggal di rumah yang tertutup?
Susahnya, sudah tahu begitu, kita masih alergi kalau dikatakan egois!
Ketika mengerjakan sholat, kita ucapkan ‘Allahu Akbar’ (Allah Mahabesar). Itu berarti, kita ini kecil sekali dihadapan Allah. Hanya Allah Ta’ala Yang Besar, yang lainnya gurem. Jika sudah merasa kecil-kecil, hingga tidak berarti sama sekali, mestinya kita sadar, bahwa kita ini tidak pantas mementingkan diri sendiri. Dihadapan-Nya, kita bukan apa-apa!
Rasulullah SAW sebelum wafat, menangis tersedu. “Ummati...ummati....!†Kata beliau SAW, sambil berlinang air mata. ‘Umatku...umatku....’. Di sini, menunjukkan betapa kepribadian beliau SAW begitu mulia. Di saat menjemput mautpun, beliau SAW masih sempat memikirkan umatnya. Padahal jarak kita dengan beliau sekarang ini sudah lebih dari 14 abad lamanya. Subhanallah.
Demikian pula ketika Rasulullah SAW hijrah, sahabat-sahabat beliau SAW, begitu besar perhatiannya terhadap kepentingan dan arti kebersamaan sesama muslim, sehingga ada yang rela menceraikan istrinya untuk ‘diberikan’ kepada sahabatnya orang-orang Muhajirin. Beberapa orang sahabat malah menyerahkan separuh lahan pertanian yang dimilikinya sebagai sumber kehidupan sahabatnya yang baru (al-Qur'an, al-Hasyr: 9). Subhanallah!
Kita? Jangankan mau memikirkan orang lain. Sesama saudara kandung saja, makanan sering dihabiskan sendiri. Apalagi jika itu kesukaan kita. Pokoknya, kalau menyangkut yang enak-enak, kita maunya didahulukan. Sedangkan jika sudah giliran yang susah, membersihkan kamar makan, kosek-kosek kamar mandi, atau yang melelahkan, kita tunjuk orang. Kita kedepankan kebutuhan kita, kita kesampingkan keperluan orang lain.
“We do not follow such system,†kata Alaa Tuti, insinyur komputer asal Libya yang ogah mengenakan dasi. ‘Kita telah mengikuti tradisi Barat’, lanjutnya. Ketika menyelesaikan studi, di universitas al-Fatah, Tripoli, salah satu perguruan tinggi terkenal di Libya, rektor universitas cukup menyampaikan ucapan selamat, kemudian menyerahkan ijazah kepada para lulusan. Demikian pula yang disampaikan Abdul Hakeem, yang menyelesaikan S2 Sastra Arab di India Selatan.
Sedari kecil, anak-anak seharusnya dibiasakan untuk tidak hidup dalam lingkungan yang memupuk pertumbuhan egoismenya. Seringkali kita memberikan puji-pujian kepada anak-anak secara berlebihan, hingga anak-anak akhirnya tumbuh ‘besar’ dan ‘sombong’. Berikan pujian yang sewajarnya, jika mereka menunjukkan prestasi dan kemajuan dalam studi. Berikan dorongan untuk memperbaiki kesalahan, bila hasil ujian mereka menurun. Tekankan untuk tidak mudah putus asa. Jangan pupuk dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada mereka!
Wisuda, bisa dilakukan dengan cara-cara lain yang lebih sederhana, tanpa mengurangi maknanya. Bukannya dengan menghambur-hamburkan uang, tenaga dan waktu. Anak-anak keluaran TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi, tidak membutuhkan pakaian kebesaran, pesta, serta mahalnya kertas sertifikat. Yang mereka butuhkan adalah, sesudah selesai studi nanti apa yang bisa mereka perbuat di lapangan sebagai manusia. Mampukah kita meyakinkan mereka akan hal ini?
Kita sudah hanyut dalam budaya yang salah. Cara-cara wisuda kita, tidak lebih dari memupuk pola pikir egois generasi muda. Budaya inilah yang tanpa kita sadari, hanya akan melahirkan generasi yang self centered-personality. Generasi yang berorientasi hanya kepada diri sendiri. Generasi yang motonya hanya ingin diperhatikan orang lain, bukannya mengajak memperhatikan orang lain.
Wallahu a’lam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

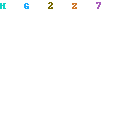
0 Response to "Wisuda Kepentingan Diri"
Posting Komentar